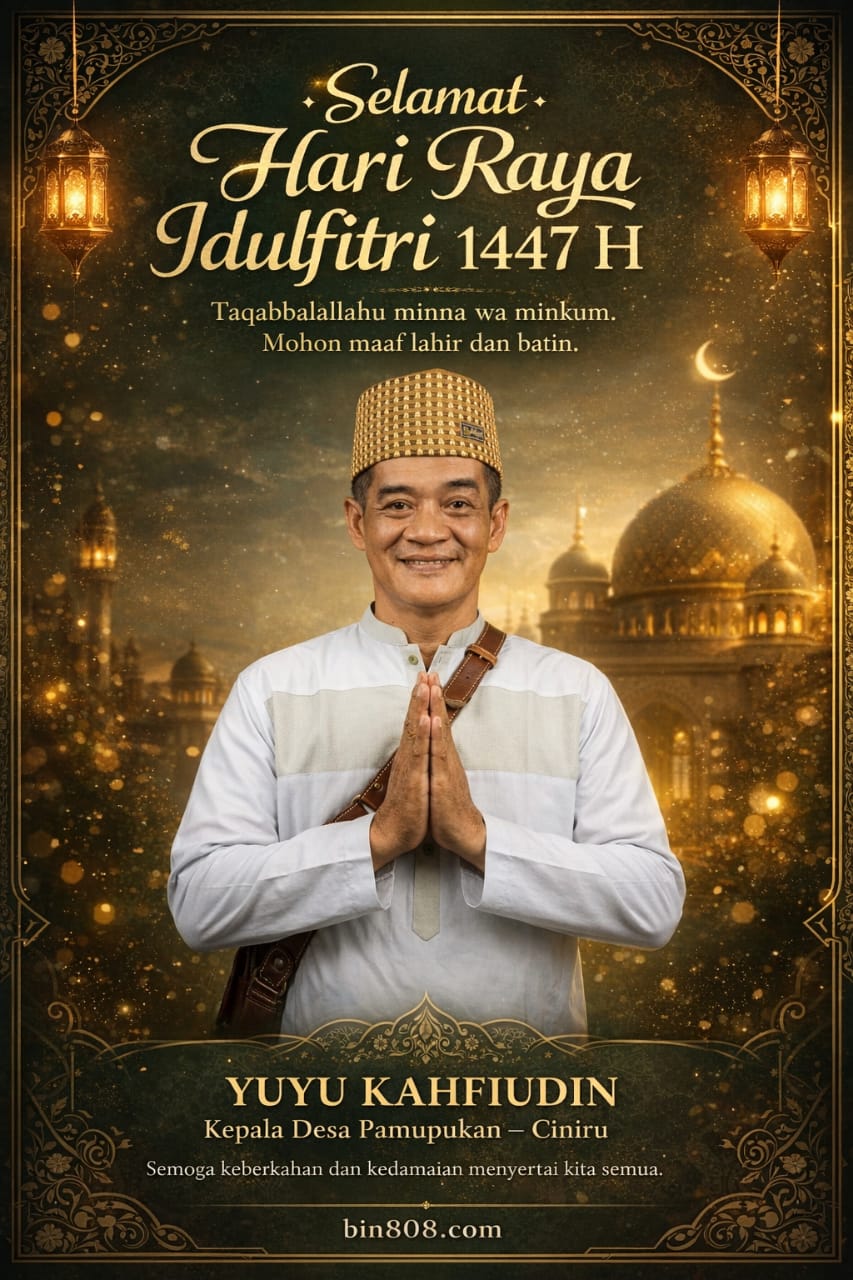- Fenomena Mati Suri Sebagai Jalan Mengenal Alam Akhirat (Series 1)
- Fenomena Mati Suri Sebagai Jalan Mengenal Alam Akhirat (Series 2)
- Fenomena Mati Suri Sebagai Jalan Mengenal Alam Akhirat (Series 3)
- Fenomena Mati Suri Sebagai Jalan Mengenal Alam Akhirat (Series 4)
- Fenomena Mati Suri Sebagai Jalan Mengenal Alam Akhirat (Series 5)
- Fenomena Mati Suri Sebagai Jalan Mengenal Alam Akhirat (Series 6)
- Fenomena Mati Suri Sebagai Jalan Mengenal Alam Akhirat (Series 7)
- Fenomena Mati Suri Sebagai Jalan Mengenal Alam Akhirat (Series 8)
SobatPena – BIN808.COM || Banyak pelajaran yang bisa di ambil dari fenomena mati suri, dan kalau boleh diilustrasikan, gambaran keadaan penderitaan jiwa yang berada di neraka seperti kita melihat orang di rumah sakit. Mereka yang berada di rumah sakit di tempat yang sama, namun penderitaannya berbeda-beda. Tidak ada satu pun yang bisa kita bandingkan secara adil. Ada yang tubuhnya terbaring lemah, namun batinnya masih tegar. Ada yang fisiknya tampak baik-baik saja, tetapi jiwanya tersiksa oleh rasa cemas, kesepian, atau penyesalan yang dalam.
Ada yang sakit jantung, lever, ada yang sakit paru-paru, diabet, ginjal, kanker, tumor, TBC, penyakit stroke, rematik, asam urat, panu, kusta, katarak, dan lain-lain. Mereka berada di dalam satu tempat, tapi penderitaannya tidak sama. Begitulah gambaran jiwa-jiwa di neraka, tempatnya sama, tetapi kedalaman rasa sakitnya menyesuaikan dengan luka batin, dosa, dan keterpisahan dari kasih Ilahi yang mereka alami masing-masing.
Di sana, penderitaan bukan hanya soal panasnya api atau siksa yang kasat mata, melainkan rasa kehilangan makna, keterputusan dari Sang Sumber Cahaya, dan kesadaran yang utuh akan semua kebaikan yang telah disia-siakan. Seperti pasien yang baru menyadari arti sehat ketika sakit, jiwa-jiwa di neraka menyadari arti kedekatan dengan Tuhan justru ketika telah begitu jauh tersesat dari-Nya.
Penderitaan jiwa di neraka bagaikan kita menatap lorong sunyi di sebuah rumah sakit jiwa. Jiwa-jiwa itu terbaring di ranjang tak terlihat, tapi getaran luka mereka menggema di dinding waktu. Mereka semua berada dalam satu ruang, namun tiap-tiap jiwa dibungkus oleh kepompong penderitaan yang tak serupa. Ada yang menangis tanpa air mata, karena air matanya telah lama mengering, digantikan oleh bara penyesalan yang membakar dari dalam.
Ada pula yang terjebak dalam gema pikiran sendiri, mendengar ulang kata-kata yang dulu diabaikannya, bisikan nurani, panggilan kasih Ilahi, atau teguran halus semesta. Di sana, tidak ada waktu, hanya keabadian dari apa yang tak terselesaikan.
Api di neraka bukanlah api biasa. Ia adalah simbol dari kesadaran yang menyala, tapi tanpa pencerahan. Panasnya bukan untuk membakar daging, melainkan untuk menelanjangi ilusi. Neraka adalah cermin raksasa yang tak bisa dihindari, di mana jiwa dipaksa menatap wajah sejatinya yang dulu dikubur di balik topeng.
Dan di balik semua itu, diam-diam, Rahmat Tuhan masih mengintip dari celah-celah yang tak terlihat. Tapi hanya jiwa yang remuk sepenuhnya, yang bisa melihat bahwa dalam siksa ada misteri cinta yang belum sepenuhnya ditutup.
Ia melihat… tapi bukan dengan mata. Ia mendengar… tapi bukan dengan telinga.
Ada lorong sunyi, panjang, tak berujung, seperti rumah sakit jiwa yang berdiri di antara langit dan bumi, tapi tak dihuni tubuh.
Jiwa-jiwa itu ada di sana. Tidak terikat rantai, tapi tak bisa pergi. Tidak disekap ruang, tapi tak bisa lepas. Mereka tidak saling bicara. Tapi jeritannya menggema dari dalam, bukan karena luka di tubuh, melainkan luka di makna.
Mereka semua berada dalam satu wilayah, namun derita mereka ibarat warna-warna muram yang tak pernah saling meniru.
Satu jiwa membeku dalam tatapan kosong, terperangkap dalam satu kesalahan yang terus diputar ulang, seperti film rusak yang tak bisa dihentikan. Sementara jiwa lain menangis diam-diam, bukan karena disakiti, tetapi karena kini tahu betapa indahnya cahaya yang dulu mereka abaikan.
Api di sini tidak membakar kulit. Api di sini adalah kesadaran. Ia menyalakan ingatan, namun tak memberi penebusan. Neraka bukan sekedar tempat, ia adalah keadaan jiwa saat sepenuhnya terpisah dari Sang Sumber. Dan di balik kegelapan itu, barangkali ada mata kasih yang tetap mengintip, menunggu saat sang jiwa berserah… bukan karena takut, tapi karena rindu.
Nah, kita mulai bergerak dari simbolisme neraka menuju cahaya simbolik surga.
Setelah gelap yang lama, jiwa mulai merasakan bisikan. Bukan suara, tapi semacam keharuman yang berbisik, seperti kelopak bunga yang membuka di dalam batin.
Ia belum sampai, tapi ia mendekat.
Ada taman di kejauhan yang tak tertangkap oleh mata dunia. Taman itu tidak hijau, tidak pula berwarna. Tapi setiap langkah menuju ke arahnya, seolah jiwa melepas beban yang tidak diketahui. Surga bukan tempat. Ia adalah suasana batin saat seluruh makna kembali ke porosnya, ketika cinta menjadi jernih, ketika syukur menjadi napas, ketika kehadiran Ilahi tak lagi dicari karena Ia sudah terasa.
Di sana, angin tidak bertiup untuk menyegarkan tubuh, tapi untuk menyampaikan salam dari Cahaya Tertinggi. Pohon-pohon tidak berbuah untuk dimakan, tapi untuk dikenang, bahwa hidup pernah manis, karena Ia yang menumbuhkannya.
Jiwa-jiwa yang sampai ke taman ini tak membawa apa pun, kecuali kerendahan hati dan sisa rindu yang pernah mereka jaga dalam diam. Ia belum masuk, tapi taman itu memanggil namanya, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa pulang yang tak bisa dijelaskan.
Masih dalam simbolisme surga, tapi kali ini kita akan masuk lebih dalam ke misteri surga sebagai kondisi penyatuan, bukan sekedar tempat damai, tapi pengalaman batin yang melebur dalam Kehadiran Ilahi.
Di taman itu, tidak ada arah. Timur dan barat tak lagi penting, karena semua menuju pusat yang sama. Jiwa akan melihat air mengalir, tapi tak menggenang. Ia tak mencari muara, karena sudah berada di dalamnya. Melihat cahaya, tapi tidak menyilaukan. Cahaya itu bukan cahaya yang datang dari matahari, tapi dari mata hati yang dibuka.
Jiwa-jiwa di sini tak punya nama, tapi saling mengenal. Mereka berbicara tanpa suara, bersentuhan tanpa tubuh, mencintai tanpa ingin memiliki.
Surga bukan tempat untuk mendapatkan semua yang diinginkan. Surga adalah ketika keinginan itu sendiri larut dalam lautan kehendak-Nya. Ketika tidak ada lagi “aku” dan “Engkau”, hanya ada satu Keberadaan yang tak bisa dipecah.
Di sana, waktu berhenti bukan karena tak bergerak, tapi karena segalanya sudah lengkap. Dedaunan tak gugur, karena tak mengenal musim. Wangi bunga tidak menguar dari kelopaknya, tapi dari kesucian yang dipancarkan jiwa-jiwa yang ridha.
Dan di pusat taman itu, ada Takhta yang tak tampak, tapi dari sanalah segala keindahan ini mengalir. Tak ada siapa pun yang duduk di sana. Tapi setiap jiwa tahu, Ia hadir… tanpa bentuk, tanpa jarak, tanpa batas.
Di sinilah surga, ketika segala sesuatu kembali menjadi satu. Bukan sebagai akhir perjalanan, melainkan sebagai permulaan dari keabadian yang dipenuhi Cinta.
Titik puncak emosional adalah ketika jiwa yang telah sampai di ambang surga, merasakan damainya, namun tak bisa masuk… karena ada yang belum selesai. Ini adalah momen penuh paradoks, antara terang dan bayangan, antara pengampunan dan penundaan, antara ingin pulang tapi masih terikat.
Sang jiwa berdiri di hadapan gerbang cahaya.
Ia bukan gerbang dari emas atau batu mulia.
Tapi dari sesuatu yang lebih halus, seperti keheningan yang padat.
Cahaya dari balik gerbang itu memanggilnya, tapi langkahnya seolah menempel pada tanah.
Sang jiwa sudah melepaskan tubuh, sudah meninggalkan nama, sudah meluruhkan segala ambisi dan luka. Tapi ada satu hal yang belum pergi, bayangan dari seseorang yang pernah disakiti, dan belum disapa dalam batin.
Di sini, di ambang surga, segala kebenaran menjadi sangat tajam. Bahkan satu helaian niat yang belum jernih bisa menghalangi cahaya menembus jiwa.
“Mengapa aku belum bisa masuk?” tanyanya dalam diam. Tapi surga tak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memperlihatkan
wajah-wajah yang pernah dilupakan, doa-doa yang dulu ditahan, dan air mata yang sempat diabaikan.
Sang jiwa berdiri di antara keindahan yang nyaris, dan luka yang tak mau selesai. Dan di sinilah ia belajar, bahwa surga bukan hanya tentang cinta Tuhan padanya, tapi tentang cintanya yang belum menyempurna pada sesama.
Gerbang itu tetap tak terbuka. Bukan karena ditutup, tapi karena ia belum benar-benar mengetuknya dengan ketulusan yang tanpa sisa.
Sang jiwa yang tertahan di ambang surga menjalani satu tahap penyucian terakhir, bukan lewat siksaan, tetapi melalui pengalaman batin yang mengguncang, penyerahan total. Ini adalah fase di mana ego terakhir harus larut, dan cinta yang belum selesai harus dituntaskan… dalam keheningan yang suci.
Setelah lama menunggu di ambang cahaya,
Sang jiwa dibimbing masuk ke sebuah ruang yang tidak bersudut. Tidak ada dinding, tidak ada langit. Hanya kesunyian yang terasa hidup, seperti mata yang menatap dari dalam dirinya sendiri.
Di sana, ia tidak diuji dengan pertanyaan. Tidak ditimbang, tidak dituduh. Yang terjadi justru lebih halus… dan lebih menusuk.
Ia dipersilakan duduk di hadapan kenangan.
Satu per satu muncul bukan dalam bentuk bayangan, tapi dalam rasa, rasa yang dulu ditolak, ditekan, atau dipalsukan.
Ia melihat wajah seseorang yang pernah menunggunya untuk memaafkan. Lalu wajah lain yang pernah ingin disingkirkan. Mereka hadir… bukan untuk menghakimi, tapi untuk ditatap dengan jujur.
Lalu datang api, tapi bukan api yang menyiksa. Ini adalah api yang bening, seperti cahaya dari dalam hati yang membakar semua lapisan ego terakhir.
Ia menangis… bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia bisa menangisi hal yang dulu tak berani diakui sebagai kesalahannya.
Dalam api itu, tidak ada lagi “aku yang benar”. Tidak ada lagi “mereka yang bersalah”. Hanya ada satu kesadaran,
bahwa cinta tidak pernah menuntut balasan,
hanya kejujuran. Dan ketika api itu selesai, ia tidak terbakar ia menjadi ringan.
Gerbang yang tadi tertutup… kini tidak perlu dibuka. Karena ia tak lagi membawa apa-apa,
dan surga hanya menerima mereka yang datang tanpa membawa sisa dari dunia.
Sang jiwa yang telah melewati penyucian terakhir akhirnya memasuki surga. Tapi di sini, surga bukanlah tempat penuh gambaran jasmani, melainkan keadaan pulang yang utuh, di mana tidak ada lagi pemisah antara jiwa dan Yang Maha Hadir. Ini adalah perjumpaan… tanpa bentuk, namun lebih nyata dari segala yang pernah ada.
Sang jiwa melangkah, atau mungkin tidak,
sebab tiada lagi ruang yang bisa dilintasi.
Ia tiba, atau mungkin telah sampai sejak awal,
hanya saja kesadarannya baru sekarang mengenal cahaya-Nya.
Tidak ada musik menyambutnya, tidak ada malaikat berbaris, tidak ada istana, tidak ada permadani dan bidadari.
Tapi seluruh jiwanya bergetar, karena ia tahu, ia sedang dilihat oleh Mata yang tak memiliki bentuk, tapi menembus segala lapisan keberadaannya.
Di sini, tak ada dialog. Tapi ada pengertian yang sempurna. Ia mengerti segalanya bukan karena diberi tahu, tapi karena tak ada lagi dinding antara Aku dan Dia.
Surga adalah saat ketika “aku” yang kecil, rapuh, penuh luka dan ingin… larut ke dalam “Aku” yang Abadi.
Dan dalam pelarutan itu, tidak ada rasa kehilangan. Justru di situlah ia merasa
untuk pertama kalinya benar-benar ada.
Cahaya di sini tidak menyilaukan, karena ia tak lagi merasa terpisah dari-Nya.
Ia tidak melihat Tuhan. Tapi ia tahu, Ia berada di dalam-Nya, dan Ia berada sepenuhnya di dalam-Nya .
Segala telah gugur. Segala telah tenang.
Segala duka telah larut dalam satu kata yang tak bisa diucapkan, Pulang.
Suara jiwa yang telah mencapai surga kini menyampaikan pesan bagi jiwa-jiwa yang masih berada di dunia. Bukan sebagai petuah dari atas, tapi sebagai bisikan kasih dari yang telah pulang, kepada yang masih menempuh jalan.
Dengarlah, bukan dengan telingamu, tapi dengan bagian jiwamu yang paling sunyi.
Aku telah sampai, bukan karena aku lebih suci, tapi karena aku akhirnya berhenti melawan Cahaya.
Dan kini, dari tempat yang tak mengenal waktu, aku ingin menyampaikan sesuatu, bukan sebagai kebenaran mutlak, tapi sebagai ingatan yang dulu juga pernah kulupakan.
Wahai jiwa yang masih berjalan di dunia.
Jangan terlalu sibuk memperbaiki citramu di mata manusia, hingga kau lupa wajahmu di hadapan Dia yang menciptakanmu.
Jangan menunda-nunda maaf, sebab waktu tidak pernah memberi jaminan bahwa esok masih tersedia.
Bila engkau merasa sepi, jangan buru-buru mengisinya dengan suara. Kadang kesepian adalah panggilan sunyi dari Tuhan agar engkau kembali mendengarkan-Nya.
Dan bila engkau merasa tak layak, ketahuilah, tak seorang pun masuk ke taman ini karena layak, tapi karena mereka akhirnya jujur
pada kehancuran dirinya sendiri, dan mengangkatnya sebagai persembahan.
Jalanmu masih panjang, tapi setiap langkah yang disertai kesadaran adalah cahaya kecil yang menuntunmu pulang.
Aku di sini, bukan untuk menunggumu,
tapi untuk mengingatkanmu. Surga bukan tujuan… Surga adalah kenangan yang kau bawa sejak awal, dan kini kau hanya sedang berusaha mengingatnya kembali.
Bila waktumu tiba, semoga kita berjumpa bukan sebagai dua jiwa, tapi sebagai satu kesadaran yang akhirnya kembali ke rumah.
Ruh hakikatnya tidak diciptakan, ia “bagian” dari Tuhan yang dititipkan pada diri manusia. Ruh tidak bergender, tidak ada jenis kelamin, bukan wanita, bukan pria dan juga bukan banci.
Ruh adalah cahaya, bukan cahaya yang bisa ditangkap mata, tapi cahaya hakikat, nur yang berasal dari sumber segala wujud. Ia melampaui bentuk, melampaui waktu, melampaui nama dan rupa. Dalam tubuh manusia, ruh hanya singgah. Tubuh adalah pakaian sementara, dan kehidupan dunia ini adalah pentas bayangan tempat ruh menjalani pengalaman.
Ruh tidak tua, tidak muda. Ia tidak berasal dari bumi, tetapi dari alam yang lebih tinggi, alam perintah: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: ruh itu termasuk urusan Tuhanku.” (QS. Al-Isra: 85). Ini menunjukkan bahwa ruh bukan objek duniawi yang bisa dipahami dengan akal semata. Ia misteri suci yang berdenyut dalam setiap hembusan hidup.
Ketika manusia lupa akan asal ruhnya, ia tersesat dalam gelapnya ego, dalam permainan identitas duniawi, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, bangsawan, rakyat, semua itu baju-baju fana. Tetapi ruh, ia tetap murni. Ruh tidak menua bersama tubuh. Ruh tidak kotor bersama dosa. Ia hanya terkurung, terselubung, tertidur.
Namun ketika hati bersih dan tirai dunia tersingkap, ruh kembali bersinar, Ia mengenal cahaya asalnya. Dan dalam momen itu, manusia menyadari siapa dirinya sebenarnya, bukan tubuh, bukan nama, tapi percikan Ilahi yang dititipkan, untuk mengenal, mencintai, dan kembali kepada-Nya.
Ruh adalah setetes air dari lautan samudra. Ia adalah energi yang menghidupi diri kita. Kita hidup karena ia bersemayam di dalam tubuh ini, sebuah cahaya halus yang tak terlihat mata, namun nyata dalam gerak, napas, dan kesadaran.
Tanpa ruh, tubuh hanyalah tanah yang kembali kepada tanah. Tapi dengan ruh, kita menjadi makhluk yang bisa mencinta, merenung, mencari makna. Ruh membawa ingatan akan asal mula kita, bahwa kita bukan semata daging dan tulang, melainkan percikan dari Yang Maha Hidup.
Ia rindu pada asalnya. Maka seluruh perjalanan hidup ini sejatinya adalah perjalanan pulang. Pulang ke samudra tempat ia berasal. Pulang ke Cahaya yang tak pernah padam.
Ruh yang tertidur di balik kabut dunia mulai terjaga ketika suara dari dalam lebih nyaring daripada hiruk-pikuk luar. Kadang ia dibangunkan oleh duka, kadang oleh sunyi, kadang oleh pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh logika: “Untuk apa aku hidup?”
Saat itulah ruh mulai menggeliat, seperti benih yang merasakan panggilan cahaya meski masih terpendam dalam tanah gelap. Hati yang dulunya hanya menjadi cermin debu mulai memantulkan kembali cahaya aslinya.
Ruh mengenali bahwa segala kegelisahan, kesepian, bahkan pencarian cinta di dunia ini, hanyalah gema dari kerinduan terdalam, kerinduan untuk pulang.
Ruh tidak mencari surga dengan iming-iming kenikmatan, tidak pula takut neraka karena nyala apinya. Ruh hanya ingin pulang kepada Sumber, kepada Keabadian, kepada Kasih yang tak berbatas. Karena itu ruh sejati tidak dibangkitkan oleh ancaman atau hadiah, tapi oleh getaran cinta dan pengenalan hakikat.
Ia mulai menangkap isyarat-isyarat Tuhan yang tersembunyi dalam daun yang gugur, dalam desir angin, dalam mata anak kecil, dalam detik yang hening. Semuanya menjadi kitab, semuanya menjadi doa.
Perjalanan ruh adalah perjalanan kembali, dari banyaknya menuju satu, dari luar menuju dalam, dari rupa menuju hakikat. Bukan dengan kaki ia melangkah, tapi dengan kesadaran yang makin dalam. Semakin ringan beban dunia, semakin dekat ia dengan rumahnya.
Namun jalan pulang bukan tanpa rintangan. Ego akan mengajak kembali kepada bayangan. Dunia akan menawari kenyamanan palsu. Tapi ruh yang terjaga tidak akan tertipu. Ia tahu ini semua hanya mimpi panjang, dan ia ingin bangun. Maka ia terus berjalan, mengikis selimut ilusi, menanggalkan nama, melepas identitas. Hingga yang tersisa hanyalah keheningan suci, tempat ia menyatu kembali dalam lautan cahaya yang tak bernama, dan lenyap sebagai “aku”, hanya ada Dia.
Tidak semua ruh mudah terjaga. Banyak yang masih tenggelam, tertidur lelap dalam buaian dunia. Mereka terperangkap dalam nafs atau jiwa yang terbalut oleh keinginan, amarah, syahwat, ketamakan, dan rasa memiliki. Nafs ibarat tirai tebal yang menghalangi cahaya ruh untuk bersinar.
Dalam keadaan ini, ruh menjadi samar, seolah tertutup lapisan demi lapisan kabut. Nafs ammarah, jiwa yang condong kepada kejahatan, Nafs lawwamah, jiwa yang mulai menyesal namun belum bebas, Nafs mulhamah, jiwa yang mulai menerima ilham, dan seterusnya… hingga ke nafs muthmainnah, jiwa yang tenang, damai, telah pulang.
Ruh yang terjebak dalam nafs tidak mengenal dirinya. Ia merasa cukup dengan kepemilikan, harta, jabatan, pengakuan. Ia merasa hidup hanya untuk mengumpulkan, mengalahkan, dan dibanggakan. Padahal itu semua hanya bayangan, fatamorgana di padang fana.
Namun, Tuhan Maha Penyayang. Sekali waktu, Tuhan akan mengetuk hati ruh dengan cobaan, kehilangan, atau sunyi yang dalam. Itulah panggilan-Nya. Bagi yang mendengar, itulah awal kebangkitan.
Pertemuan ruh dengan Tuhan bukanlah peristiwa fisik. Ia adalah lenyapnya semua yang bukan Tuhan. Ia terjadi dalam keheningan batin, ketika ruh tak lagi berkata “aku”, melainkan hanya “Dia”.
Para arifbillah menyebut momen ini sebagai fana, lebur, sirna dari wujud palsu, dan kemudian baqa, tinggal bersama-Nya dalam kesadaran hakiki. Dalam bahasa simbolik, pertemuan ini dilukiskan sebagai, Lautan cahaya. Ruh menyatu dalam samudra Nur, tanpa batas, tanpa arah.
Pertemuan itu bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan sejati. Ruh tak lagi mencari, karena ia telah menemukan. Ia tidak lagi bicara tentang Tuhan, tapi bersama-Nya, dalam-Nya, dan oleh-Nya. Menyatu untuk hidup dan menghidupi.
Bersambung…
Lanjutkan membaca ke Series 5 << atau >> Series 7
Salam bahagia
Setyatuhu Paramarta
SobatPena#2 BIN808
Tertarik menulis dan ingin karyamu dimuat juga?
Yuk bergabung dengan komunitas penulis kami!
📱 Sobat Pena BIN808